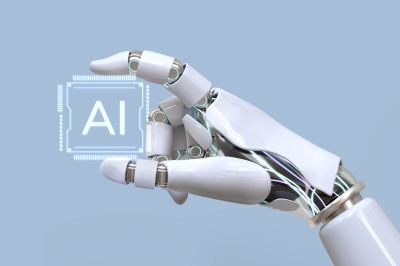Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Pajak Seadil Zakat. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Pajak Seadil Zakat. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Rasanya Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tanpa fatwa itu seperti bakso tanpa kuah: kenyang sih bisa, tapi sensasinya tidak greget. Hanya terasa sebentar di mulut, tak tersisa di otak.
Sejak kelahirannya pada 26 Juli 1975, lembaga ini memang sudah mengukir reputasi sebagai produsen fatwa.
Keputusan keagamaannya, yang bunyinya kadang lebih dramatis dari sinetron Lebaran, sudah jadi trade mark MUI. MUI itu ya fatwa.
Jadi ketika Munas XI MUI di Ancol pekan lalu mengetukkan palu dan mengumumkan fatwa haramnya negara memungut pajak untuk hal-hal tertentu, publik sontak seperti baru bangun sahur: antara bingung, senang, dan bertanya-tanya, "Lho, ini beneran?"
Tapi, bagi pemerintah? Bayangkan, setelah mendengar fatwa itu, betapa tegangnya wajah para pejabat pajak dari pusat sampai petugas kelurahan. Dari Menteri Keuangan yang biasanya sigap menghitung defisit, sampai Pak RT yang rajin narik PBB sambil ngopi di pos ronda.
Semuanya tiba-tiba berpotensi jadi pelaku pelanggaran syariat jika tetap menjalankan tugas mereka. Wuih, betapa dahsyat efeknya. Anda bisa membayangkan rapat staf direksi DJP berubah rasa jadi rapat tabligh akbar, yang seorang pun tak berani menyebut kata "pajak" tanpa berwudu dulu.
Mari masuk dulu ke ruang Munas di Ancol yang berlangsung seperti sidang akademik sekaligus reuni nasional para ulama lintas ormas. Para kiai berdiskusi dengan gaya santun namun bermata elang, para profesor agama membawa catatan seperti pengacara di final mahkamah konstitusi.
Para pengurus MUI dari seantero Nusantara hadir dengan wajah serius seakan sedang merumuskan ulang masa depan republik. Gedung ballroom beraroma parfum elegan dan kopi Arabica, tapi suasananya lebih mirip ruang darurat teologis.
Baca juga: Pengamat Selamat Ginting: Mahasiswa Harus Jadi Garda Terdepan Hadapi Perang Generasi Kelima
Setiap kalimat disimak, setiap dalil diberi perhatian, setiap angka ditelaah seolah-olah menentukan keselamatan umat sedunia. Dari sinilah keputusan-keputusan penting dicetak, mulai dari arah dakwah kebangsaan sampai batas konsumsi barang haram.
Dan yang paling heboh tentu saja keputusan bernomor 01/Munas XI/2025 tentang "Pajak Berkeadilan". Bunyinya kurang lebih demikian: Memungut pajak pada kebutuhan pokok _(dharuriyat)_ dan barang atau layanan primer rakyat adalah haram.
Juga, pajak hanya boleh diberlakukan kepada harta, kepemilikan, atau aktivitas finansial yang produktif dengan nilai di atas nisab zakat. Ada tambahan: zakat yang sudah dibayarkan umat Islam wajib menjadi pengurang kewajiban pajak.
Terakhir, memungut pajak kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria tersebut adalah tidak sah secara syar’i dan mengundang konsekuensi dosa. Begitu kalimat itu diketuk, peserta forum mengangguk, kamera wartawan sibuk mencatat dan memotret.
Sementara publik di luar gedung spontan berdebat antara tepuk tangan dan geleng-geleng kepala. Tak sedikit yang tersenyum lebar ketika mendengar sembako dinyatakan bebas pajak, rumah hunian tidak boleh dipajaki tiap tahun, dan orang yang hartanya belum setara 85 gram emas seharusnya tak boleh disentuh kewajiban pajak.
Apalagi kalau sudah bayar zakat masih harus bayar pajak, dianggap tidak fair — karena itu sama saja dengan pesan di telinga umat: jangan dobel pembayaran, nanti dobel perih di akhirat.
Adil, elegan, dan yang pasti bikin yang sudah lama kesel sama PPN pada telur dan beras langsung sujud syukur. Bahkan orang Swedia yang pajaknya bikin keringat dingin pun mungkin akan merasa iri: "Aha... Kalau begitu kami sebaiknya pindah ke Indonesia."
Baca juga: Bupati Majalengka Serahkan 3.492 SK PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Tak Ada Penurunan Hak Pegawai
Namun tentu saja di balik gegap gempita ini ada debat intelektual panjang yang tak kalah mendebarkan. Gagasan pajak sebagai zakat — atau zakat sebagai pajak — bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Fatwa MUI itu bukan baru.
Cendekiawan Masdar Farid Mas’udi sudah menuliskannya 15 tahun lalu dalam bukunya "Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat". Negara tak boleh menjalankan pungutan di luar moral distribusi kesejahteraan.
Kalau zakat ditujukan untuk delapan asnaf, maka logika keuangannya berlaku juga untuk pajak. Artinya, pajak mestinya dikeluarkan untuk manusia: yang fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Maka muncul pula tuntutan filosofis yang bikin para ahli ekonomi angkat alis: kalau PBB tidak produktif, mengapa dipungut tahunan? Kalau sembako dasar kehidupan, kenapa diperlakukan seperti _luxury goods_?
Sayangnya, kenyataan ekonomi ini ibarat cinta tak direstui orang tua. Fatwa memang berkumandang dari Ancol, tapi APBN tetap ditagih dari Senayan. Pemerintah masih harus membangun jalan, membayar guru, menggaji tentara, mengurus kesehatan, dan entah apa lagi.
Ketika fiskal bertemu fikih, kadang yang muncul adalah tabrakan, bukan paduan suara. Menteri Keuangan butuh pemasukan, MUI menuntut keadilan syariah, rakyat ingin harga murah, dan semua ingin masuk surga bersama-sama.
Terdengar ideal — sampai tabel Excel bertemu ayat Al-Qur’an, lalu keduanya saling melotot memperebutkan supremasi. Dan fatwa, karena sifatnya hanya hukum fiqih yang tak dapat stempel politik, ya hanya jadi pilihan moral.
Tapi, mungkin saja di masa depan kita akan melihat format baru: Dirjen Pajak sekaligus Amil Zakat Nasional, slip PPN diganti form "Sertifikat Kemaslahatan Ummah", dan musyawarah anggaran negara disiarkan live.
Bisa jadi ada standing ovation ketika pemerintah berhasil memungut pajak tanpa mengundang murka Tuhan. Atau sebaliknya, fatwa baru diterbitkan karena ada aturan perpajakan yang dianggap kelewat kreatif.
Tetapi mungkin juga, inilah momen kita untuk refleksi. Bahwa negara bukan hanya mesin pendapatan, dan agama bukan hanya daftar larangan.
Bahwa pajak dan zakat — sekeras apa pun perdebatan — pada dasarnya sama-sama ingin satu hal: rakyat hidup sejahtera, bukan sengsara; adil dan merata.
Kalau kelak pemerintah berhasil menghapus ketidakadilan fiskal, membebaskan yang lemah, dan memastikan beban hanya ditanggung mereka yang betul-betul mampu, maka kita tak hanya berhasil mengikuti fatwa, tapi juga mengikuti hati nurani.
Sampai di sini, kadang tragedi fiskal bisa berubah jadi hikmah kebangsaan yang meneduhkan. Dan siapa tahu, yang selama ini terasa sebagai tagihan bisa perlahan menjadi bukti cinta negara pada rakyatnya — bukan sebaliknya. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 27/11/2025

 2 hours ago
1
2 hours ago
1