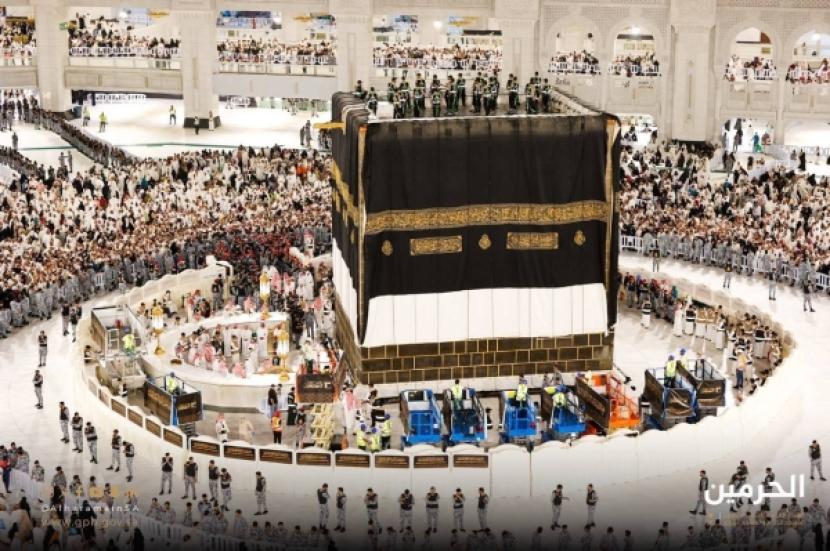Umar Wachid B. Sudirjo
Umar Wachid B. Sudirjo
Politik | 2025-11-02 01:05:23

Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan oleh sebuah video sederhana: Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terlihat sedang mengaji di dalam mobil. Video itu viral. Judul-judul berita kemudian bermunculan, mulai dari “Menteri Keuangan yang Taat Beribadah” hingga “Pejabat Rendah Hati yang Mengaji di Tengah Kesibukan.” Reaksi publik pun beragam — sebagian menyanjung, sebagian sinis, sebagian lagi sekadar menonton tanpa peduli makna di baliknya.
Namun, yang menarik bukan semata pada video itu sendiri, melainkan pada mengapa hal semacam itu bisa menjadi berita besar. Mengapa “Purbaya mengaji” harus menjadi viral, sementara di tempat lain rakyat miskin yang menangis karena lapar tidak mendapatkan ruang pemberitaan yang sama?
Jawabannya mungkin sederhana, tapi getir: karena pejabat yang mengaji adalah fenomena langka, sementara orang miskin yang lapar adalah kenyataan sehari-hari. Dan yang biasa, sayangnya, tidak laku dijadikan berita.
Citra dan Kebiasaan yang Menjadi Tontonan
Masyarakat Indonesia tampaknya tidak pernah bosan dengan pola pencitraan. Kita mudah terbius oleh sesuatu yang dianggap “berbeda”, “menyentuh”, atau “layak dipuji”. Padahal sering kali yang kita lihat hanyalah fragmen — potongan citra yang sengaja dipilih untuk dikonsumsi publik. Di negeri ini, “keberbedaan” sering kali menjadi bahan jualan emosional. Dan di tangan media, fragmen itu dibentuk menjadi kisah: seorang pejabat membaca Al-Qur’an di mobil, seolah menjadi simbol keteladanan baru.
Padahal, bisa jadi itu hanya potret kecil dari rutinitas pribadi yang kebetulan terekam. Namun begitu sampai di ruang publik, ia menjelma narasi besar. Media bukan sekadar menampilkan kenyataan, tetapi membingkainya, menafsirkannya, dan akhirnya mengarahkan cara publik melihatnya.
Panggung Politik dan Pemeran Citra
Inilah panggung politik lengkap dengan karakter pemainnya. Ada yang benar-benar antagonis, ada pula yang antagonis tapi berperan manis. Ada yang tampil dengan keaslian, ada yang hadir dengan skenario. Dan publik, seperti penonton sinetron, terus dihidangkan drama tanpa jeda.
Jika dibandingkan, cara Purbaya berbeda dengan cara Dedi Mulyadi atau Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7. Purbaya tampak lebih natural, tidak terlihat menyiapkan kamera atau narasi. Sedangkan gaya Jokowi — yang kini banyak diadopsi oleh Dedi Mulyadi — sering kali terlihat lebih terencana, nyaris seperti pementasan yang diatur oleh sutradara komunikasi politik. Dari gaya berjalan, sapaan ke rakyat kecil, hingga pilihan lokasi kunjungan, semua tampak menyatu dalam strategi simbolik.
Bukan berarti pencitraan selalu buruk — karena setiap pemimpin butuh citra — tetapi ketika citra menjadi panggung utama, substansi mudah tergeser. Dan publik pun lebih sering menilai dari kemasan ketimbang isi.
Antara Purbaya yang Nyata dan Purbaya Versi Media
Maka muncul pertanyaan mendasar: Siapakah sebenarnya Purbaya? Apakah ia benar-benar sosok yang tenang, religius, dan sederhana seperti yang tampak di video itu? Ataukah ia hanya Purbaya versi media, hasil olahan narasi dan pencitraan yang dikonstruksi oleh mesin pemberitaan?
Di dunia yang serba visual, seseorang tidak lagi hadir sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai versi yang tampak di layar. Ia bisa benar-benar Purbaya yang nyata — dengan segala kejujuran dan kebiasaannya — atau hanya sosok yang dibentuk oleh lensa kamera, cahaya, dan framing berita.
Dalam situasi seperti ini, figur publik kehilangan sebagian hak atas dirinya sendiri. Ia menjadi milik publik, milik wacana, milik narasi yang terus bergerak. Publik melihat bukan manusia, tapi simbol yang sudah ditafsirkan.
Rocky Gerung dan Fenomena Kritik Publik
Terlepas dari itu semua, kritik Rocky Gerung terhadap Purbaya juga sempat mencuat. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa kritik tersebut tidak terkait dengan video viral mengaji. Rocky mengkritik Purbaya dalam konteks pernyataan ekonomi dan kebijakan publik, terutama soal “17 + 8 Tuntutan Rakyat” serta penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN, yang menurutnya merupakan langkah keliru dan tidak konsisten dengan semangat transparansi fiskal.
Namun di luar substansi ekonomi itu, kritik Rocky tetap menarik untuk dibaca secara sosial-psikologis. Ia bisa dipahami sebagai bentuk keterkejutan seorang intelektual terhadap manuver atau gaya komunikasi pejabat ekonomi yang mulai tampil di panggung publik. Rocky terbiasa melihat pejabat teknokratik berbicara data dan angka, bukan menonjolkan sisi personal atau simbolik. Maka ketika muncul figur seperti Purbaya — yang sekaligus rasional dan hangat secara sosial — sebagian pengamat bisa merasa bingung atau curiga. Dalam hal ini, kritik Rocky bisa dibaca bukan sekadar sebagai penolakan, tetapi reaksi terhadap perubahan wajah pejabat ekonomi yang tidak biasa tampil “humanis.”
Ketika Fakta Tunduk pada Narasi
Maka kabar viral tentang Purbaya yang mengaji di dalam mobilnya bisa jadi hanyalah bagian dari drama media dalam membentuk persepsi. Di tangan media, realitas tidak lagi berdiri apa adanya. Ia disulap menjadi kisah yang menyentuh, mengharukan, atau mengagumkan — sesuai selera pasar. Publik bukan lagi diajak berpikir, tetapi diarahkan untuk merasakan sesuatu. Dan dari rasa itulah lahir kekaguman massal yang tidak lagi membutuhkan kebenaran.
Barangkali Purbaya memang mengaji, barangkali tidak — tetapi yang jelas, publik telah lebih dulu percaya pada versi media, bahkan sebelum mencari versi manusia. Inilah zaman di mana citra lebih berkuasa daripada fakta, dan kebenaran tunduk pada narasi yang paling laku dibagikan.
Media dan Hilangnya Nurani Kemanusiaan
Di luar itu semua, media hari ini tak lagi menjadi corong masyarakat secara keseluruhan, melainkan corong bagi apa yang menguntungkan. Berita kini diukur bukan dari nilai kemanusiaan, tetapi dari nilai klik, viewer, dan engagement.
Maka wajar bila tangisan rakyat miskin tak lagi menarik — sebab dari mana media akan memperoleh keuntungan? Tak ada sponsor di balik perut lapar, tak ada iklan di sela air mata. Yang ada justru beban moral, karena sebelum menulis berita, seorang jurnalis lapangan mungkin harus merogoh kocek sendiri untuk menolong. Akibatnya, penderitaan rakyat hanya hidup di pinggir layar, kalah sorot oleh kamera yang membidik pejabat berpeci dan Al-Qur’an di pangkuannya.
Media yang dulu menjadi penjaga nurani publik, kini berubah menjadi panggung dagang citra dan emosi. Bukan lagi bertanya “apa yang benar,” melainkan “apa yang ramai.” Dan di tengah euforia itu, realitas sosial yang getir perlahan tersingkir oleh kabar yang manis.
Publik yang Terlatih Menonton
Masalahnya bukan hanya pada media, tapi juga pada kita — para penontonnya. Kita telah terlatih untuk mencari tontonan, bukan kebenaran. Kita lebih cepat tergerak oleh potongan video tiga puluh detik ketimbang laporan panjang tentang kelaparan di pelosok. Kita terhibur oleh simbol religius, tapi jarang menguji makna moral di baliknya.
Media membentuk selera publik, dan publik memberi makan algoritma media. Siklus ini berputar tanpa akhir — menciptakan budaya “bising tapi hampa.” Dan di tengah hiruk pikuk itu, kebenaran menjadi semakin sunyi.
Penutup: Antara Realitas dan Ilusi
Kita mungkin tak bisa memastikan apakah Purbaya yang mengaji di mobil itu benar-benar spontan atau bagian dari dinamika yang lebih luas. Namun yang lebih penting bukanlah apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita memaknainya.
Sebab di era informasi ini, realitas bisa dimanipulasi tanpa perlu berbohong. Cukup ubah sudut pandang, pilih momen, beri judul yang manis — maka lahirlah narasi baru. Dan publik pun percaya.
Mungkin besok media akan menulis:
“Sandal jepit Purbaya putus, tapi ia tetap berjalan kaki dengan senyum.”
Padahal, bisa jadi memang sandalnya putus, tidak lebih dari itu. Namun di tangan media, peristiwa kecil berubah menjadi simbol kesederhanaan dan keteladanan.
Itulah kekuatan media: menciptakan makna di antara fakta. Dan di situlah letak bahayanya, sekaligus keindahannya. Karena pada akhirnya, yang disebut “tokoh publik” bukan lagi manusia sepenuhnya — melainkan bayangan dirinya yang telah dipoles oleh lensa, narasi, dan tafsir publik.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 8 hours ago
3
8 hours ago
3