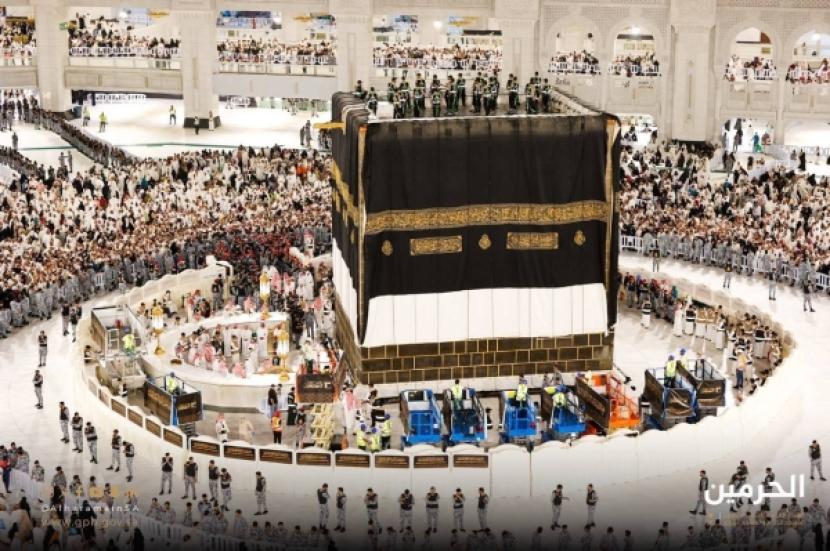Riverzh
Riverzh
Teknologi | 2025-11-01 20:09:12
 Sumber: https://kominfo.kuburaya.go.id/10-istilah-ai-yang-perlu-anda-ketahui
Sumber: https://kominfo.kuburaya.go.id/10-istilah-ai-yang-perlu-anda-ketahui
Oleh: Zharra Kumala, Mahasiswa Universitas Airlangga
Idealnya, ruang kelas menjadi arena pertukaran gagasan yang hidup dan kritis, terutama di jenjang perguruan tinggi. Namun, realitas yang terjadi justru berbanding terbalik. Banyak mahasiswa menyampaikan presentasi yang terasa kaku, artifisial, dan minim orisinalitas. Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Di satu sisi, dosen kerap melepas tanggung jawab dengan dalih penerapan model student-centered learning. Di sisi lain, mahasiswa kebingungan karena diminta menyajikan materi yang bahkan belum mereka pahami.
Dari situ, pertemuan pertama mereka dengan teknologi kecerdasan buatan pun dimulai. Menurut survei Didaktita, sebanyak 65,5 persen mahasiswa mengaku cukup sering menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Artinya, penerapan pembelajaran mandiri tanpa pendampingan ketat rentan dimanfaatkan untuk manipulasi akademik melalui ChatGPT atau platform AI lainnya. Model ini sejatinya merupakan bagian dari kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, namun ironisnya justru menjadi bumerang ketika lonjakan penggunaan AI meningkat pesat pascapandemi.
Kini, fenomena serupa merebak di berbagai kampus di Indonesia. Ketika diminta membuat bahan presentasi, banyak mahasiswa langsung bergantung pada AI ketimbang menelusuri buku atau jurnal ilmiah. Akurasi isi bukan lagi prioritas; yang penting tugas selesai tepat waktu. Dalam sesi presentasi, ketika muncul pertanyaan, mereka kembali mengandalkan AI untuk menjawab karena sebenarnya tidak memahami konsep dasarnya.
Alasan yang kerap muncul pun seragam: beban tugas menumpuk, tenggat waktu ketat, serta persepsi bahwa dosen hanya menilai hasil akhir secara formalitas. Masalah ini semakin kompleks ketika dosen tidak melakukan pengujian mendalam terhadap pemahaman mahasiswa. Sebagian dosen merasa nyaman dengan pola tersebut, terjebak dalam zona aman yang menyamakan self-learning dengan zero supervision. Padahal, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Ketika proses belajar hanya berorientasi pada hasil instan, kompetensi mahasiswa menjadi dangkal dan tidak siap menghadapi tuntutan dunia kerja.
Lebih jauh, muncul pula dilema etis yang belum diantisipasi secara serius oleh institusi pendidikan. Banyak kampus belum memiliki panduan yang jelas mengenai batas penggunaan AI dalam konteks akademik. Akibatnya, setiap dosen menerapkan standar yang berbeda-beda. Di satu kelas, penggunaan ChatGPT dianggap inovatif; di kelas lain, justru dikategorikan sebagai bentuk kecurangan. Ketidakselarasan ini menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa dan memperlebar kesenjangan literasi digital antarprogram studi. Padahal, kemampuan menggunakan teknologi seharusnya disertai pemahaman tentang integritas akademik dan tanggung jawab moral.
Dalam konteks sosial, penggunaan kecerdasan buatan juga berdampak pada cara manusia berinteraksi. Ketika mahasiswa terbiasa menyelesaikan persoalan melalui mesin, ruang diskusi dan kerja sama antarmanusia semakin menyempit. Kebiasaan mengandalkan jawaban instan mengikis kemampuan berkomunikasi, berargumentasi, dan membangun kedekatan emosional yang lazim muncul dalam proses belajar kolaboratif. Secara perlahan, teknologi menggantikan peran manusia sebagai mitra berpikir.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi digital. Negara ini tergolong berada pada kesenjangan digital tingkat kedua, yang ditandai dengan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya kemampuan menilai dan menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital sejatinya mencerminkan sejauh mana seseorang mampu memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan teknologi secara kritis. Tanpa kemampuan tersebut, masyarakat hanya akan menjadi pengguna pasif yang bergantung pada hasil mesin tanpa memahami proses di baliknya.
Secara kognitif, ketergantungan pada AI juga menghambat perkembangan fungsi berpikir tingkat tinggi. Proses berpikir kritis yang melibatkan aktivitas otak depan dalam menganalisis data nonlinier dan memecahkan masalah kompleks menjadi terabaikan. Otak manusia bekerja berdasarkan prinsip use it or lose it, kemampuan yang jarang digunakan akan menurun. Ketika proses sintesis dan analisis diserahkan sepenuhnya pada AI, daya analitis manusia perlahan tumpul. Hasil studi PISA tahun 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari 80 negara menjadi bukti nyata lemahnya kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital generasi muda Indonesia.
Situasi ini ironis karena filosofi student-centered learning sejatinya bertujuan menumbuhkan kemandirian berpikir, bukan sekadar kemampuan menyalin dan menempel informasi. Meskipun berbagai perangkat antiplagiasi berbasis AI telah dikembangkan, efektivitasnya tetap terbatas sebab teks yang dihasilkan AI bersifat baru dan sulit terdeteksi. Persoalan utamanya bukan lagi plagiarisme, melainkan hilangnya proses pemahaman yang sejati. Sudah saatnya peran dosen dalam pendidikan tinggi dikembalikan ke hakikatnya.
Dosen tidak hanya menjadi fasilitator tetapi juga pendamping yang membantu tumbuhnya cara berpikir. Hadirnya teknologi seharusnya tidak menggeser peran itu, sebaliknya malah memperkaya inovasi akan cara mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswa. Tugas dosen tidak hanya memastikan mahasiswa mengumpulkan tugas, tetapi menuntun mereka memahami proses. Proses inilah yang membentuk nalar dan karakter intelektual yang tidak bisa diserahkan pada mesin.
Ketergantungan mahasiswa pada kecerdasan buatan sebenarnya cermin dari lemahnya sistem belajar yang masih menekankan hafalan dan hasil akhir. Hal ini terjadi karena mahasiswa melihat bahwa faktanya nilai lebih dihargai daripada prosesnya. Padahal, tanpa menalar, mahasiswa akan menjadi pasif terhadap teknologi. Pembelajaran membuka ruang yang lebih nyata, sekaligus menciptakan makna belajar sebagai proses berpikir, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi melainkan oleh seberapa dalam pemahaman mahasiswa akan arti makna belajar itu sendiri. Karena faktanya dunia kerja menuntut lebih dari sekadar kemampuan digital, mereka menuntut empati, kebijaksanaan, dan keberanian mengambil keputusan secara etis. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi yang bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu membangun nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Kecerdasan buatan seharusnya membantu manusia menjadi lebih bijak, bukan menggantikan kemampuan analitiknya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 18 hours ago
3
18 hours ago
3